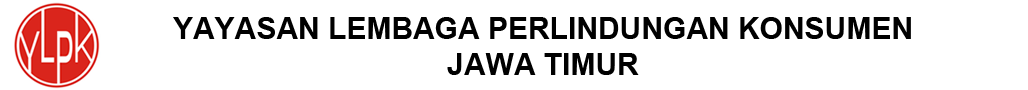HARGA obat di Indonesia tergolong paling mahal di dunia. Kenapa? Sebab, sebagai pasar obat terbesar keempat di dunia, kita tidak memproteksi harga obat dan masih lebih banyak menggunakan bahan baku impor.
HARGA obat di Indonesia tergolong paling mahal di dunia. Kenapa? Sebab, sebagai pasar obat terbesar keempat di dunia, kita tidak memproteksi harga obat dan masih lebih banyak menggunakan bahan baku impor.
Sementara itu, obat paten yang beredar lebih banyak diproduksi di luar negeri, khususnya negara-negara maju yang upah minimum regional (UMR) buruhnya pasti jauh lebih mahal ketimbang di sini. Tiga pasar besar, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, dan India, melakukan itu.
Hasil penelitian Health Action International (HAI) Penang pada 1995 terhadap 22 jenis obat yang paling banyak digunakan di 29 negara Asia Pasifik membuktikan bahwa harga obat di negeri kita tercinta ini memang yang termahal di kawasan ASEAN. Pemicunya, pemakaian obat di Indonesia tergolong tidak rasional.
Menurut definisi yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 1987, pemakaian obat yang rasional adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Digunakan sesuai dengan indikasi penyakit; (2) Tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau masyarakat luas; (3) Diberikan dengan dosis yang tepat; (4) Diberikan dalam interval waktu yang tepat; (5) Lama pemberiannya tepat; serta (6) Obat yang diberikan harus efektif, aman, dan mutunya terjamin.
Tiga tahun sebelumnya, konferensi WHO di Nairobi pada 1985 juga menegaskan bahwa obat merupakan kebutuhan kedokteran dan klinik. Dengan demikian, pemberiannya harus sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dosis dan lamanya pemberian obat. Oleh karena itu, harga obat harus cukup murah sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Di Indonesia, kriteria-kriteria tersebut belum diterapkan secara baik dan benar. Baik oleh konsumen (pasien) maupun provider (perusahaan farmasi, dokter, rumah sakit, dan yang lainnya).
Ketidakrasionalan pasien dalam mengonsumsi obat terutama disebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Hal itulah yang membuat mereka lantas cenderung serampangan dalam menggunakan obat, bahkan berani mengabaikan saran dokter atau petugas medis yang kompeten dan menggunakan obat secara berlebih, menurut cara dan analisis sendiri (self diagnose).
Dari sisi provider, seperti dokter dan rumah sakit, ketidakrasionalan itu beragam. Mulai adanya kecenderungan memberikan obat yang mahal, padahal ada yang jauh lebih murah dan cukup efektif, sampai pada jumlah obat yang diberikan. Banyak dokter yang cenderung memberikan beberapa macam obat kepada seorang pasien, meski dia tahu bahwa penyakit si pasien bisa disembuhkan dengan satu atau dua jenis saja, misalnya.
Hal tidak rasional lain yang banyak dilakukan dokter dan rumah sakit adalah adanya kebiasaan mengarahkan pembelian obat di apotek tertentu. Tindakan itu menjadi semakin sulit disebut rasional ketika ternyata apotek tersebut milik si dokter sendiri.
Fakta lain yang lebih mengerikan dalam masalah obat itu adalah masih banyaknya perusahaan farmasi yang mengelabui pasien dengan cara memperbanyak indikasi obat produksi mereka. Caranya, satu jenis obat yang semula indikasinya hanya dua (katakanlah A dan B), tiba-tiba muncul di pasaran dengan indikasi yang lebih banyak (A, B, C, D dan E).
Bersamaan dengan itu, mereka juga melakukan tindakan yang lebih kejam dengan cara menyembunyikan lebih banyak efek samping obat tersebut. Hal-hal seperti itu tak akan terjadi kalau fungsi kontrol oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terhadap label MIMS (monthly index of medical specialist) tidak melemah.
Saatnya Proteksi
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pernah mencoba menerobos mahalnya harga obat itu. Melalui Permenkes No 10 Tahun 2008, beliau mengharuskan semua obat yang beredar di Indonesia diproduksi di dalam negeri.
Dari sisi ekonomi nasional, peraturan itu mungkin bisa memberikan dampak positif. Yakni, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Namun, dari sisi harga obat, ketentuan tersebut tidak menjamin penurunan harga yang signifikan. Penyebabnya paling tidak ada dua. Pertama, bahan bakunya masih harus diimpor. Kedua, lokasi pabrik tidak banyak berpengaruh pada harga obat paten. Jadi, pemindahan lokasi pabrik bisa berdampak sebaliknya (jadi lebih mahal) karena pengusaha harus melakukan investasi baru. Ke mana mereka akan membebankan nilai investasinya kalau bukan ke harga obat?
Perlu dicatat, dalam pasar farmasi di Indonesia yang nilainya mencapai Rp 28 triliun, sebanyak 90 persen dikuasai obat paten, baru sisanya yang 10 persen oleh obat generik. Artinya, sebagian besar belanja kesehatan di Indonesia dihabiskan untuk obat yang tidak rasional. Padahal, efektivitas antara obat paten dan obat generik relatif tidak berbeda. Sebab, obat generik tersebut secara substantif merupakan obat paten yang masa patennya telah habis dan dapat diproduksi masal, tanpa keharusan membayar royalti paten lagi.
Masih terbatasnya penggunaan obat generik terutama disebabkan masih minimnya sosialisasi obat tersebut, baik kepada publik maupun para petugas pelayanan kesehatan (dokter dan rumah sakit). Khusus penyedia pelayanan kesehatan, kalaupun mereka sudah tahu tentang obat generik, banyak di antara mereka yang enggan memberikan obat generik kepada pasien karena memberikan margin (keuntungan) yang kecil.
Nasib konsumen obat di Indonesia semakin diperparah oleh maraknya peredaran obat palsu. WHO memperkirakan, 10 persen obat yang beredar di seluruh dunia adalah palsu. Sementara itu, laporan United States Trade Representative (USTR) dalam 301 Report tahun 2008 memperkirakan, 25 persen obat yang beredar di Indonesia adalah palsu.
Secara ekonomis, obat palsu merugikan pemerintah dan industri farmasi. Bagi konsumen, selain kerugian ekonomi, obat palsu memperburuk kondisi pasien, bahkan bisa mengakibatkan kematian.
Menyediakan obat yang rasional dari sisi harga menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, khususnya Menteri Kesehatan Endang Sulastri Adiningsih. Mengampanyekan penggunaan obat generik merupakan salah satu cara untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman obat yang tidak rasional. Maka, Menkes harus selalu mengingatkan penyedia pelayanan kesehatan agar mendahulukan penggunaan obat generik daripada obat paten kepada pasien. (*)
*) Djoko Santoso dr SpPD K-GH PhD , dokter spesialis ginjal-hipertensi, tinggal di Surabaya
(sumber : Jawa Pos)