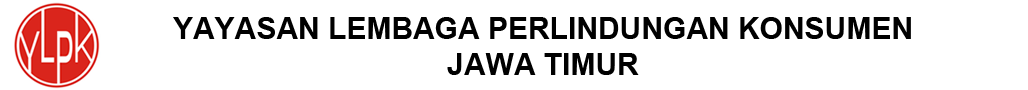Masalah harga/tarif merupakan masalah hilir. Seharusnya pemerintah cerdas mencari solusi lain dari sisi hulu. Jika pemerintah secara radikal mencari solusi di sisi hulu, kenaikan harga secara ekstrem tak perlu dilakukan.
Hiruk-pikuk tahun politik dengan pesta pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden sangat mengharu biru masyarakat Indonesia. Kebijakan publik yang digagas pemerintah pun tampak terkontaminasi oleh aura tahun politik. Tidak mengherankan jika selama dua tahun (2018-2019) kebijakan publik tersandera oleh tahun politik. Akibatnya, atmosfer perlindungan konsumen selama masa itu hanya janji manis tidak naiknya tarif komoditas publik strategis, seperti tarif listrik, harga bahan bakar minyak, iuran BPJS Kesehatan, bahkan cukai rokok. Alasannya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun alasan sesungguhnya adalah alasan populis menjelang pemilihan umum. Terbukti setelah pemilihan usai, masyarakat diperlakukan sebaliknya: masyarakat ketiban pulung karena harus menanggung kenaikan berganda pada 2020. Keberpihakan negara terhadap perlindungan konsumen hanyalah kamuflase. Konsumen mendapat pil pahit berupa kenaikan harga atau tarif berbagai komoditas publik, bahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.
Pemerintah tampak tidak kreatif bahkan malas mencari solusi selain menaikkan tarif. Pemerintah begitu gampang mentransfer beban kepada konsumen. Masalah harga/tarif merupakan masalah hilir. Seharusnya pemerintah cerdas mencari solusi lain dari sisi hulu. Jika pemerintah secara radikal mencari solusi di sisi hulu, kenaikan harga secara ekstrem tak perlu dilakukan, termasuk untuk BPJS Kesehatan sekalipun.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bermula dari kesalahan pemerintah sendiri karena sejak awal rancangan BPJS Kesehatan adalah merugi akibat besaran iuran belum mencerminkan struktur biaya yang sebenarnya. Namun pemerintah tidak secara serius mengulik dengan kebijakan dari sisi hulu yang sifatnya fundamental. Pemerintah tidak melakukan pembenahan kebijakan untuk mewujudkan gaya hidup masyarakat yang lebih sehat. Contohnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengendalian Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak mati suri karena ditolak oleh kalangan industri makanan dan minuman. Pemerintah melakukan pembiaran konsumsi gula, garam, dan lemak semakin mewabah, padahal perilaku hidup tidak sehat dominan menjadi penyebab utama berbagi jenis penyakit katastropik yang selama ini menggerus finansial BPJS Kesehatan.
Dalam kasus pengendalian konsumsi rokok/tembakau lebih parah lagi. Pemerintah nyaris abai sehingga konsumsi rokok semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Saat ini, jumlah perokok aktif di Indonesia tidak kurang dari 35 persen dari total populasi. Setiap tahun tidak kurang dari 500 miliar batang rokok diproduksi. Belum lagi fenomena rokok elektrik di kalangan generasi muda yang kian mengkhawatirkan. Tragisnya, selama dua tahun terakhir, pemerintah tidak menaikkan cukai rokok. Padahal cukai rokok adalah instrumen pengendali utama untuk konsumsi rokok, khususnya di kalangan rentan. Nihilnya kenaikan cukai rokok demi pertimbangan politik adalah sebuah tragedi bagi kesehatan publik karena menjadi dorongan kuat naiknya konsumsi rokok. Kenaikan cukai rokok pada 2020 sebesar 23 persen hanyalah kado kecil yang tidak bermakna untuk mewujudkan perilaku hidup sehat masyarakat.
Setali tiga uang adalah kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 VA dan menerapkan tarif otomatis untuk golongan 1.300 VA ke atas. Wujud konkret pencabutan subsidi atau menerapkan tarif otomatis adalah kenaikan tarif. Padahal, merunut pada data tarif listrik di ASEAN, tarif listrik di Indonesia termasuk termahal ketiga di ASEAN. Seharusnya kenaikan tarif listrik tidak harus dilakukan jika pemerintah mampu mengendalikan harga energi primer, khususnya batu bara. Harga domestic market obligation batu bara yang dipatok pemerintah sebesar US$ 70 per ton masih terlalu tinggi. Seharusnya harganya bisa diturunkan karena margin keuntungan pengusaha batu bara masih terlalu besar.
Adapun dalam konteks ekonomi digital, pemerintah memberikan kado lumayan positif untuk melindungi konsumen, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tren perdagangan elektronik (e-commerce) selama lima tahun terakhir cukup dominan. Walau aturan tersebut terlambat, patut diapresiasi. Data pengaduan konsumen di YLKI selama lima tahun terakhir menunjukkan pengaduan yang berkaitan dengan e-commerce menduduki peringkat tiga besar. Artinya, dari sisi perlindungan konsumen, e-commerce masih menyimpan persoalan yang serius.
Yang juga menyisakan cerita pilu adalah pinjaman online. Sistem bunga dan dendanya telah menjadikan konsumen sebagai sapi perah dan perundungan data pribadi yang amat dahsyat. Korbannya berjatuhan, bahkan sampai terjadi bunuh diri, perceraian, dan pemecatan dari tempat kerja. Masifnya pengaduan pinjaman online, selain akibat literasi digital konsumen lemah, terjadi karena mandulnya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal yang absurd adalah dalih OJK bahwa pinjaman online ilegal bukan tanggung jawabnya.
Jadi, basis keberpihakan pemerintah pada kepentingan publik dan perlindungan konsumen pada 2019 hanyalah angin surga alias kamuflase politik dan pada 2020 hak konsumen dieksploitasi sedemikian rupa.
Artikel ini pertama kali terbit di Koran Tempo; 26 Des 2019 dan Tempo.co. Silahkan kunjungi
TULUS ABADI Ketua Pengurus Harian YLKI
Source: YLKI