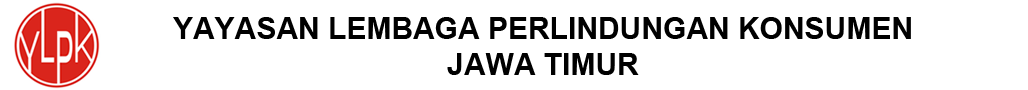Sungguh tidak nyaman menjadi konsumen di negeri ini. Bukan saja sulit menggapai kesejahteraan hidup, tetapi, bahkan kualitas hidup warga negeri ini justru digerogoti oleh negara. Sebuah institusi yang seharusnya mengejawantahkan welfare state bagi warga negaranya.
Sungguh tidak nyaman menjadi konsumen di negeri ini. Bukan saja sulit menggapai kesejahteraan hidup, tetapi, bahkan kualitas hidup warga negeri ini justru digerogoti oleh negara. Sebuah institusi yang seharusnya mengejawantahkan welfare state bagi warga negaranya.
Jelas, ini merupakan bentuk kekerasan (violence) yang sejatinya tidak bisa dibiarkan. Indikasi betapa negara bukan saja ‘tidak hadir’ tetapi malah melegalisasi perampokan bagi income warga negaranya, adalah keputusan untuk menaikkan tarif jalan tol.
Awal bulan ini, bukan tembang ‘September Ceria’ yang akan dinikmati bagi pengguna jalan tol tetapi ‘September derita’, karena Pemerintah menaikkan tarif tol hingga 20 persen, di 13 ruas jalan tol di Indonesia.
Keputusan ini jelas membuat konsumen pengguna jalan tol meradang, bukan kepalang. Bayangkan, tiba-tiba konsumen harus merogoh kocek Rp 6.000, dari biasanya Rp 2.000, untuk lintasan jalan tol yang sangat pendek. Selain itu, antrian mengular ketika hendak memasuki pintu gerbang jalan tol, makin membuat psikologi pengguna jalan tol mendidih ke puncak ubun-ubun.
Perasaan semacam ini bukan saja dilakoni oleh konsumen kebanyakan, tetapi juga membuat seorang pejabat negara lain gundah-gulana. Via pesan pendek (sms) yang dikirim kepada penulis, pejabat negara itu mengatakan, “Tarif tol membingungkan! Dari pintu Veteran ke Pintu Pondok Aren, biasanya bayar Rp 2.000. Sekarang masuk bayar Rp 6.000, keluar bayar Rp. 1.500, jadi total Rp 7.500”.
Namun, ditengah kemarahan publik pengguna jalan tol, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, begitu entengnya mengemukakan alasan kenaikan tarif jalan. Tanpa guilty feeling sedikitpun, Joko menandaskan bahwa kenaikan tarif jalan tol harus dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup pengelola dan investor jalan tol. Tarif jalan tol juga harus dilakukan untuk ‘menjawab’ terhadap laju inflasi yang terjadi.
Keputusan ini merupakan antiklimaks terhadap kebijakan harga (pricing policy) di negeri ini. Betapa tidak? Sebab, keputusan ini tanpa tedeng aling-aling hanya mendasarkan pada laju inflasi ansich, alias menghilangkan eksistensi stakeholder utama, yaitu konsumen pengguna jalan tol. Bahkan, ketika Pemerintah hanya mendasarkan laju inflasi untuk menaikkan tarif suatu komoditas publik, selain menabrak prinsip-prinsip keadilan, juga merupakan keputusan yang ‘bodoh’.
Ada dua argumen sederhana (commen sense) untuk bisa merontokkan alasan Joko Kirmanto menaikkan tarif jalan tol, yaitu : pertama, dimanapun dan kapan pun juga, setiap kebijakan harga yang adil seharusnya mempertimbangkan kepentingan dua stakeholders, yaitu kepentingan pengelola/investor jalan tol dan atau kepentingan konsumen sebagai pengguna jalan tol.
Disinilah rasa keadilan itu ditabrak oleh seorang Joko Kirmanto, karena hanya memperhatikan kepentingan pelaku usaha (pengelola/investor jalan tol). Lalu kepentingan konsumen pengguna jalan tol di buang kemana Pak Menteri? Jika Pak Menteri seorang yang berstatus pejabat publik, seharusnya kemampuan membayar (ability to pay) dan kemauan membayar (willingness to pay) konsumen juga menjadi pertimbangan utama. Sekalipun pengguna jalan tol adalah kaum bermobil ria, tetapi soal seberapa kemampuan membayarnya tetap diperlukan.
Dalam konteks jalan tol, yang urgen untuk dipertanyakan adalah aspek kemauan membayarnya. Aspek ini memang tidak terkait dengan jumlah kocek yang berada di di dompet konsumen, tetapi terkait dengan nilai kemanfaatan yang diperoleh konsumen saat menggunakan jasa jalan tol. Ini mendesak untuk dipertanyakan karena secara empiris saat ini nilai manfaat jalan sudah menurun drastis, khususnya jalan tol dalam kota.
Pada konteks inilah kenaikan tarif tol sudah tidak relevan lagi. Untuk apa masyarakat konsumen harus membayar kemacetan di dalam jalan tol yang makin menggila? Dan, trend ke depan, konsumen pengguna jalan tol akan terus ditelikung dengan kemacetan, karena luas jalan tol tidak akan mampu mengejar pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang tak kalah gilanya.
Belum lagi aspek layanan yang lain yang tidak kalah kedodorannya, misal derek gratis yang tidak gratis, serta pedagang asongan yang lenggang- kangkung menjajakan dagangannya. Atau banyaknya rest area yang justru menjadi penyumbang tingginya kemacetan.
Dari sisi normatif yuridis, kenaikan tarif tol menabrak pakem dan konvensi hukum. Lazimnya, kenaikan tarif hanya dikukuhkan dengan keputusan presiden (Kepres). Tetapi untuk jalan tol mengapa dikukuhkan dengan sebuah undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan? Bahkan, sesungguhnya Pemerintah terjadi kekeliruan yang sangat fatal dalam menafsiran UU tentang Jalan. UU tentang Jalan hanya mengatakan bahwa setiap dua tahun sekali tarif jalan bisa disesuaikan.
Kata ‘disesuaian’ tidak harus diterjemahkan dengan ‘kenaikan’, bahkan bisa sebaliknya (diturunkan). Masalahnya, ‘disesuaikan’ dengan apa saja? Jika disesuaikan dengan kondisi empiris dan kemanfaatan jalan tol. maka tak ada alasan pembenar apapun untuk mengerek tarif jalan tol.
Klausul bahwa ‘disesuaikan’ setara dengan kenaikan adalah tengara yang sangat terang-benderang betapa aturan ini lahir dari ‘ketiak’ pengelola/investor jalan tol. Sementara hak-hak konsumen pengguna jalan tol teronggok dalam tong sampah birokrasi.
Akhirnya, bisa disimpulkan dengan sangat mudah, bahwa kenaikan tarif tol merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang tidak elok untuk dibiarkan. Mengharapkan Pemerintah dan parlemen untuk mengubah dan merevisi regulasi yang ada, bak menggantang asap saja. Tidak ada jalan lain, publik pengguna jalan tol harus melakukan perlawanan secara radikal.
yang tidak elok untuk dibiarkan. Mengharapkan Pemerintah dan parlemen untuk mengubah dan merevisi regulasi yang ada, bak menggantang asap saja. Tidak ada jalan lain, publik pengguna jalan tol harus melakukan perlawanan secara radikal.
Salah satu jalur yang bisa digunakan untuk melawan bentuk arogansi ini adalah dengan gugatan class action. Konsumen jalan tol harus bersatu mendobrak keangkuhan kekuasan ini.YLKI pun siap menjadi pendamping konsumen atas perampasan hak tersebut. Jangan biarkan negara dan kroni-kroninya secara telanjang merampas dan menginjak-injak hak publik (konsumen).
Tulus Abadi, Anggota Pengurus Harian YLKI.