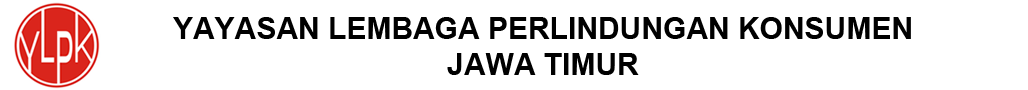Sejak 30 tahun terakhir, Indonesia masih berkutat dengan sulitnya mengatur peresepan dokter, yang sebagian besar adalah ”obat-obat latah” atau me-too drugs. Obat-obat ini dikemas dan dipasarkan layaknya obat ”paten”, padahal tak lain adalah obat-obat generik yang ”bermerek”. Akibatnya, harga obat resep di Indonesia tergolong termahal di ASEAN, bahkan di dunia! Akhir November 2009, diantar Heru Santosa, Sekretaris I Kedubes RI untuk Kuba, Kompas sempat mengunjungi beberapa fasilitas kesehatan dan sebuah apotek di Kota Havana.
Sejak 30 tahun terakhir, Indonesia masih berkutat dengan sulitnya mengatur peresepan dokter, yang sebagian besar adalah ”obat-obat latah” atau me-too drugs. Obat-obat ini dikemas dan dipasarkan layaknya obat ”paten”, padahal tak lain adalah obat-obat generik yang ”bermerek”. Akibatnya, harga obat resep di Indonesia tergolong termahal di ASEAN, bahkan di dunia! Akhir November 2009, diantar Heru Santosa, Sekretaris I Kedubes RI untuk Kuba, Kompas sempat mengunjungi beberapa fasilitas kesehatan dan sebuah apotek di Kota Havana.
Walaupun didera kesulitan ekonomi sejak bubarnya Uni Soviet, tetap saja fasilitas kesehatan dasar Kuba jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Pusat kesehatan masyarakat tingkat rukun warga di Kuba jauh lebih lengkap dibanding puskesmas tingkat kecamatan di Indonesia.
Dengan merata, murah/gratis, dan baiknya layanan kesehatan serta pendidikan tak mengherankan jika Kuba berada di peringkat 50-an teratas untuk Indeks Pembangunan Manusia (HDI), sementara Indonesia justru terpuruk di peringkat ke-114. Kita coba bandingkan harga salah satu obat esensial, misalnya metformin, obat lini pertama diabetes tipe-2. Obat ini lazim dikenal dengan merek dagang Glucophage, obat ”originator” temuan Bristol-Myers-Squibb.
Di apotek di Jakarta, Glucophage, yang sudah lewat masa patennya, untuk satu strip berisi 10 tablet 500 mg dipatok dengan harga Rp 14.100, sedang untuk merek lain yang sebenarnya hanya ”obat latah” dihargai Rp 11.000, dan obat generik dengan tulisan Metformin hanya Rp 3.000/10 tablet.
Di apotek untuk warga Kuba, harga satu dus obat Metformina berisi 10 strip yang masing-masing berisi 10 tablet 850 mg harganya hanya 1 peso Kuba atau sama dengan Rp 400. Berarti satu strip obat generik metformin di Kuba buatan perusahaan Cipla, India, (walaupun berdosis lebih besar) harganya cuma Rp 40! Ini berarti pula harga metformin di Indonesia lebih mahal 75 kali dibanding di Kuba.
Tentu kita bisa berkilah, Kuba adalah negara sosialis komunis. Dan, Kuba dikenal sebagai negara yang tak menghargai hak paten dan hak atas kekayaan intelektual. Namun, seyogianya Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasila adalah negara kesejahteraan (welfare state) dan sosial demokratis, bukan negara dengan ekonomi liberal.
Menurut Direktur Utama PT Kimia Farma M Syamsul Arifin, saat ini 80 persen bahan baku obat-obatan di Indonesia diimpor dari India dan China. Anehnya, walaupun harga bahan baku impor ini murah, setelah diproduksi menjadi ”obat-obat latah” oleh industri farmasi Indonesia harganya jadi berlipat kali lebih mahal dibanding harga obat-obat yang sama di India dan China. Ini tak lain karena industri farmasi di Indonesia masih tetap terjangkit ”penyakit” mencari rente (rent seeking), mencari keuntungan sebesar-besarnya yang telah berlangsung sejak era Orde Baru.
Mengontrak dokter
Dengan margin keuntungan yang amat besar—karena bahan baku yang supermurah sebab pembuatnya di India dan China umumnya tidak melakukan riset untuk menemukan molekul-molekul bahan aktifnya— harga ”obat latah” atau generik bermerek di Indonesia dijual dengan harga tak banyak beda dengan harga obat ”originator”-nya, bahkan kadang-kadang bisa lebih tinggi.
Penyebabnya, industri farmasi swasta nasional Indonesia lebih agresif ”mengontrak” para dokter dibanding industri farmasi asing. Tak mengherankan jika belasan industri farmasi swasta nasional mendominasi pangsa pasar obat resep Indonesia, jauh meninggalkan sekitar 30 industri farmasi asing.
Awal tahun 2000, Bristol-Myers-Squibb dan Hoechst menduduki peringkat ke-6 dan ke-10 (Kompas, 22/11/2000), tetapi belakangan hanya Pfizer yang masuk dalam 10 besar industri farmasi. Fenomena ”kontrak-mengontrak” industri farmasi-dokter sudah berlangsung lama.
Namun, istilah industrio-medical complex baru pertama kali diungkapkan oleh Prof dr Iwan Darmansjah ketika ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Farmakologi di FK UI tahun 1983 sebagai otokritik terhadap profesi kedokteran (Kompas, 23/5/1983).
Tahun 1970-an hingga awal 1980-an praktik ”memberi imbalan” kepada para dokter lebih banyak dilakukan oleh industri farmasi asing. Namun, belakangan, industri farmasi swasta nasional—termasuk di Indonesia—makin ”pintar” dan lebih jago menghalalkan segala cara untuk merayu para dokter agar meresepkan ”obat-obat latah” produksi mereka.
Selama dekade 1980-an hingga awal 1990-an Kompas amat sering menurunkan berita di halaman 1 tentang mahalnya harga obat di Indonesia dan perlunya mengatur praktik peresepan obat oleh para dokter. Hasilnya, antara lain, sampel obat dilarang. Departemen Kesehatan (ketika itu) pun mulai memperkenalkan istilah ”obat generik” tahun 1984, disusul dibuatnya ketentuan resep dokter untuk pasien ”berkantong tipis” yang tak lain adalah daftar 80-an obat esensial.
Kekuasaan absolut
Selama sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih menganut fee for service (pasien harus membayar sendiri jasa dan produk kesehatan, termasuk obat)—belum berupa asuransi kesehatan—semuanya tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar. Hal itu berlangsung terus hingga kini. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/-I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah juga tak akan menyentuh masyarakat yang masih amat banyak berobat ke praktik dokter/rumah sakit swasta.
Kunci pengendalian harga obat dan kerasionalan peresepan obat di Indonesia adalah pada dokter yang terikat sumpah dokter/etika kedokteran. Industri farmasi adalah entitas bisnis, sehingga sulit mengharapkan mereka menjalankan praktik bisnis yang ”beretika” dan tidak melakukan penyuapan.
Obat resep (ethical drugs) adalah satu-satunya komoditas di dunia yang tidak memberikan kebebasan kepada konsumen/ pasien untuk memilih sendiri. Semuanya bergantung pada pena dokter. ”Kekuasaan absolut” inilah yang tak jarang disalahgunakan oleh sebagian dokter kita, yang sudah melupakan darma panggilannya sebagai ”penyelamat/pemelihara kehidupan”.
Jika ingin melakukan reformasi sektor dan sistem kesehatan nasional di Indonesia, resep dokter harus boleh diaudit. Tak ada salahnya Indonesia meniru cara Filipina yang pada masa pemerintahan Presiden Corazon Aquino mengeluarkan Undang Undang Generik (Generic Law). Peraturan itu mewajibkan para dokter menulis resep dengan nama generik/bahan aktif obat. Kebebasan memilih diserahkan ke konsumen dengan bimbingan petugas apotek.
Awalnya para dokter protes (baca Prescription for Change, 1992). Beranikah Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih melakukan terobosan ini? Tentu ia perlu meminta dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Selama niat baik mengutamakan kepentingan pasien—seperti yang tersurat dalam sumpah dokter—tidak ada alasan bagi para dokter dan IDI menentangnya.
Sumber : Kompas