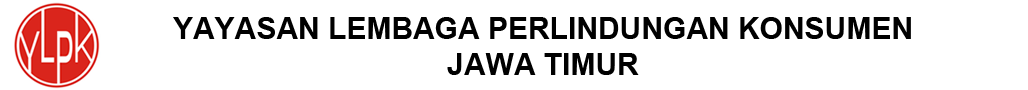BEBERAPA bulan terakhir terbetik wacana bahwa pemerintah akan menata ulang pemberian subsidi gas elpiji 3 (tiga) kg atau lazim disebut tabung melon. Tentu saja wacana ini menimbulkan sengkarut lumayan serius di ranah publik.
Sebab, terminologi menata ulang, wujud konkretnya adalah pencabutan subsidi, bahkan kenaikan tarif. Di saat ekonomi sedang lesu darah, pertumbuhan ekonomi melorot; wacana ini tentu saja mengerek sentimen publik yang cukup keras.
Lalu, di manakah keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil dan sektor ekonomi mikro seperti UKM dan UMKM? Itulah kira-kira pertanyaan yang mengemuka.
Jika penataan ulang itu dimaknai sebagai pencabutan subsidi, maka pada konteks makroekonomi politik hal tersebut sangat boleh jadi mencerminkan ada ketidakadilan ekonomi pemerintah.
Sebab, di satu sisi, pemerintah gembar-gembor efisiensi subsidi, tetapi di sisi lain pemerintah menggelontorkan subsidi untuk taipan sawit sebesar Rp7,5 triliun. Aksi tersebut jelas kebijakan kontraproduktif, bahkan sesat pikir, karena bisa memicu genderang perang yang lebih keras dengan Uni Eropa, yang mengembargo produk sawit Indonesia ke telatah Eropa.
Plus berlawanan isu lingkungan global sebab industri sawit telah mengakibatkan deforestasi (penggundulan hutan) yang amat serius di Indonesia. Apalagi, pada konteks undang-undang tentang energi, subsidi energi adalah hak warga negara, khususnya bagi rumah tangga miskin.
Sejatinya kebijakan migrasi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg (2004), yang ditukangi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah hal positif. Yang pasti, waktu itu pemerintah banyak menghemat subsidi dari sektor energi. Selain itu, gas elpiji juga jauh lebih ramah lingkungan daripada minyak tanah.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun merekomendasikan gas elpiji untuk keperluan domestik rumah tangga daripada minyak tanah, dan apalagi kayu bakar. Itu artinya, gas elpiji juga merupakan produk energi fosil yang lebih ramah terhadap kesehatan walau awal mula pemberlakuan gas elpiji 3 kg puluhan nyawa konsumen harus melayang karena insiden kebocoran gas elpiji yang menimbulkan ledakan.
Tetapi, dalam berjalannya waktu, kebijakan gas melon ini banyak melahirkan berbagai anomali dan dalam batas tertentu malah menjadi benalu bagi finansial negara. Pertama, kebijakan gas melon memicu impor gas elpiji yang sangat dahsyat. Faktanya, pascapemakaian massal gas melon mengakibatkan impor gas elpiji melambung tinggi, lebih dari 60%.
Hal ini terjadi karena kemampuan kilang PT Pertamina dalam memproduksi gas elpiji masih sangat minim. Solusinya, untuk memenuhi kebutuhan domestik gas elpiji adalah impor. Karena bergantung pada pasokan impor, maka harga gas elpiji pun amat bergantung pada harga pasar internasional (standar Saudi Aramco).
Anomali berikutnya adalah distribusi gas elpiji yang terbuka. Sejatinya awal dioperasikannya tabung melon, distribusinya bersifat tertutup, yakni dengan kartu kendali. Hanya dengan kartu kendali itulah, tabung gas melon bisa dibeli oleh konsumen rumah tangga miskin.
Ironisnya, kartu kendali itu hanya seumur jagung karena setelah itu distribusi tabung melon bersifat terbuka alias semua orang boleh membeli tabung melon: apa pun status sosialnya. Bahkan banyak restoran papan atas pun mencaplok gas elpiji 3 kg untuk bisnisnya. Kelompok konsumen yang tinggal di apartemen pun tak malu-malu mengonsumsi gas melon.
Dan, anomali ketiga adalah manakala harga gas elpiji 12 kg ditetapkan atas harga keekonomiannya. Harga gas elpiji 12 kg menjadi sangat mahal dan sangat jomplang dengan harga gas 3 kg. Akibatnya, banyak konsumen elpiji 12 kg yang turun kelas menjadi pengguna gas elpiji 3 kg.
Bagaimana tidak turun kelas jika di pasaran terdapat dua jenis komoditas yang sama, tetapi harganya berbeda. Perilaku konsumen semacam ini tidak bisa disalahkan, malah sesuai dengan hukum pasar. Moralitas dan etika sosial menjadi mitos belaka. Fenomena ini mampu menggerus 15-20% pangsa pasar elpiji 12 kg dan artinya mendistorsi pengguna gas elpiji 3 kg. Si kaya dan si miskin berebut bersama menggunakan gas melon, dan si kaya akan keluar sebagai pemenangnya.
Lalu, bagaimana menyikapi wacana kebijakan pemerintah yang akan mengubah pola distribusi gas elpiji 3 kg menjadi distribusi tertutup, plus harganya akan disesuaikan harga pasar?
Di atas kertas, wacana itu cukup rasional. Sebagaimana saya singgung di awal bahwa awalnya pendistribusian gas melon memang bersifat tertutup dengan kartu kendali. Tegasnya, hanya berbasis kartu kendali itulah, konsumen bisa membeli gas melon, tidak sembarang orang bisa membelinya, seperti sekarang.
Dengan kata lain, wacana itu sama artinya akan mengembalikan khitah semula: distribusi tertutup! Namun, jika pemberian subsidinya berupa cash transfer, bisa memicu persoalan yang lebih rumit. Pertama, potensi salah sasaran sangat besar, kecuali pemerintah (TNP2K) mampu melakukan pemutakhiran data secara presisi, tidak tumpang tindih seperti sekarang.
Apakah pemerintah berani memberikan jaminan untuk hal tersebut, dan bagaimana mekanisme pengawasannya? Kedua, disalahgunakan untuk membeli komoditas lainnya misalnya membeli rokok. Prevalensi merokok pada rumah tangga miskin sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada biaya untuk konsumsi lauk-pauk, dan atau pendidikan.
Apalagi, harga rokok masih murah dan bisa dibeli eceran. Jadi cash transfer untuk subsidi gas elpiji potensi untuk disalahgunakan sangat besar. Dan, konsumen pun gigit jari karena harga gas elpiji 3 kg di pasaran sudah melambung tinggi.
Dari sisi energi, hal yang harus diperhatikan pascadistribusi tertutup dan harga gas elpiji disesuaikan harga pasar, penghematan dana subsidinya akan digunakan untuk apa? Padahal, pemerintah akan mengantongi penghematan subsidi sangat signifikan, yakni Rp50 triliun.
Dana sebanyak ini idealnya harus dikompensasikan untuk sektor energi secara langsung, yakni untuk pengembangan energi baru terbarukan, dan atau untuk membangun jaringan gas (jargas) untuk memasok gas alam ke rumah tangga. Jargas di satu sisi harganya sangat murah, tetapi diperlukan investasi yang mahal untuk membangun pipa gas. Karena itu, dana Rp 50 triliun bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jargas tersebut.
Selain itu, pembangunan jargas juga akan menekan tingginya impor gas elpiji yang terus membubung tinggi, yang kini mencapai tidak kurang dari delapan metrik ton per tahun. Kecuali PT Pertamina mampu membangun kilang baru dan merevitalisasi kilang-kilang minyaknya yang sudah menua agar mampu menghasilkan gas elpiji sehingga impor gas elpiji tidak diperlukan lagi (tidak bergantung pada impor).
Ketergantungan kita terhadap energi fosil harus segera diakhiri, termasuk dominannya penggunaan gas elpiji. Mengingat, selain harganya akan makin mahal, baik karena impor atau cadangannya makin menipis, juga destruktif terhadap lingkungan global. Secara ekstrem subsidi untuk energi fosil juga bukan hal produktif yang tidak visibel untuk dipertahankan.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk bahan bakar yang ramah lingkungan yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg harus dijadikan momen untuk memasok bahan bakar ramah lingkungan yang berbasis EBT. Dan, karena itu, perlu insentif untuk mewujudkannya, dan dana penghematan subsidi sebesar Rp50 triliun bisa digunakan untuk hal tersebut.
Artikel ini telah terbit di SINDONEWS.COM, Selasa; 18 Februari 2020. Silahkan kunjungi link di sini
TULUS ABADI Ketua Pengurus Harian
Source: YLKI